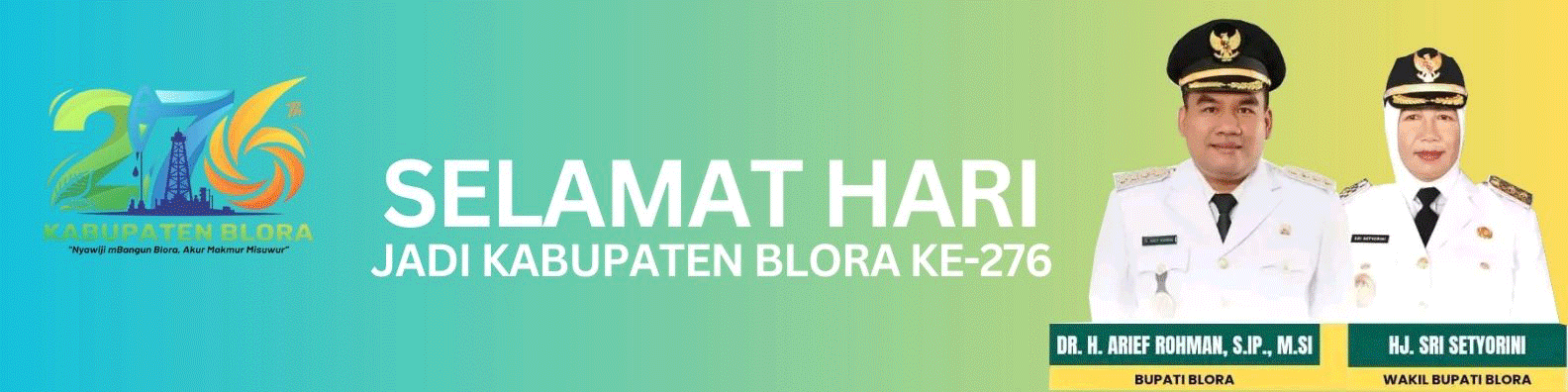Samin Surosentiko bukanlah seorang tokoh militer, melainkan hanya seorang petani biasa dari Desa Ploso Kediren, Randublatung, Blora, Jawa Tengah. Mbah Suro, melawan pemerintah kolonial Belanda.
Nama Samin Surosentiko yang biasa kita kenal selama ini bukanlah nama aslinya, sebab sesungguhnya nama aslinya adalah Raden Kohar yang merupakan keturunan Kanjeng Pangeran Arya Kusumowinahyu.
Kisah perlawanan yang dimulai dari seorang Samin Surosentiko ternyata mampu mengguncang sistem hukum kolonial Belanda hingga ke akar-akarnya.
Awal mula Samin melawan pemerintah kolonial adalah ketika pejabat/petinggi Belanda menerapkan pajak tanah, pajak hasil bumi, dan merampas hutan jati untuk kepentingan industri kayu mereka, Samin tidak tinggal diam dan memilih jalan yang berbeda dari yang biasa manusia lain lakukan.
Bukan menggunakan sejata api, pedang ataupun bambu runcing, tetapi dengan filosofi sederhana yang revolusioner dengan menolak mengakui legitimasi hukum penjajah, menolak membayar pajak, dan menolak untuk bekerja dengan Belanda.
Perlawanan yang tidak biasa, Samin dan pengikutnya yang kini disebut dengan ”Sedulur Sikep” mempraktikan perlawanan pasif. Mereka tidak hanya menolak mengakui kolonial, tetapi juga menolak melakukan kekerasan.
Prinsip mereka sederhana yaitu, ”Hukum adat lebih tinggi daripada hukum kolonial; tanah, air, dan hutan adalah milik bersama bukan milik pemerintah ataupun individu; hidup harus dijalani dengan jujur dan tidak boleh mengambil hak orang lain”.
Ada percakapan saat Samin ditagih membayar pajak oleh kolonial, kurang lebih seperti ini, ”Tanah ini bukan milik Belanda, jadi kenapa harus bayar?”. Lalu ketika diminta untuk mengakui kekuasaan kolonial, mereka hanya membalah senyum dan diam, atau bahkan menjawab dengan kalimat logis yang membuat pejabat/petinggi Belanda frustasi.
Bagi Belanda, tindakan Samin dan pengikutnya ini dianggap melawan hukum. Pajak adalah kewajiban, hutan adalah milik negara (dalam hal ini Negara Kolonial), dan siapa pun yang menolak tunduk akan dikenai sanksi. Namun, bagi Samin dan pengikutnya, aturan Belanda hanyalah “aturan orang asing” yang tidak memiliki legitimasi moral di tanah Jawa.
Konflik ini menciptakan benturan bagi kedua sistem hukum, hukum adat samin lebih mengutamakan kepemilikan komunal, kejujuran dan juga kesetaraan. Sedangkan hukum kolonia Belanda lebih mengutamakan kontrol negara, kepemilikan privat, dan juga kewajiban untuk membayar pajak.
Akibat dari benturan ini, banyak dari pengikut saminisme ini dipenjara, sebab dianggap membangkang terhadap kebijakan kolonial. Naman semua itu tidak membuat mereka menyerah, mereka tetap konsisten dengan prinsip mereka, bahkan seringkali membingungkan petugas penjara dengan sikap tenang dan ucapan filosofis/logis mereka.
Gerakan samin dan pengikutnya mungkin tidak mengangkat senjata, tetapi gerakan mereka memiliki dampak yang cukup besar. Beliau menunjukkan pada rakyat jawa, bahwasannya melawan penjajah tidak selalu harus menggunakan kekerasan. Saminisme menjadi simbol perlawanan moral, maksudnya perlawanan yang membongkar legitimasi kekuasaan kolonial di mata rakyat.
Belanda akhirnya menyadari bahwa memenjarakan mereka (pengikut ajaran saminisme), tidak menghentikan penyebaran ide-ide mereka. Justru semakin ditekan, ajaran tersebut semakin populer di kalangan petani yang lelah dengan pajak dan juga kerja paksa.
Kini, lebih dari se-abad setelah Samin Surosentiko meninggal/wafat, ajarannya masih hidup di sebagian masyarakat Blora, Pati, dan sekitarnya (daerah lain). Prinsip “nguwongke” atau “memanusiakan manusia”, tetap menjadi pegangan, dan semangat perlawanan tanpa kekerasan menjadi inspirasi bagi gerakan sosial modern.
Saminisme bukan hanya sekedar sejarah lokal, itu adalah bukti bahwa keberanian tidak selalu diukur dari kekuatan senjata, tetapi dari keteguhan hati untuk nmempertahankan prinsip awal. Ditengah gempuran hukum kolonial yang keras, gerakan saminisme mampu membuktikan bahwa suara diam pun bisa mengguncang sebuah sistem yang tampak kokoh.
Penulis Khairul Anisa, Mahasiswi Prodi Ilmu Hukum Universitas Terbuka (Salut Cepu Raya) Semester V.
Referensi : Berbagai sumber.